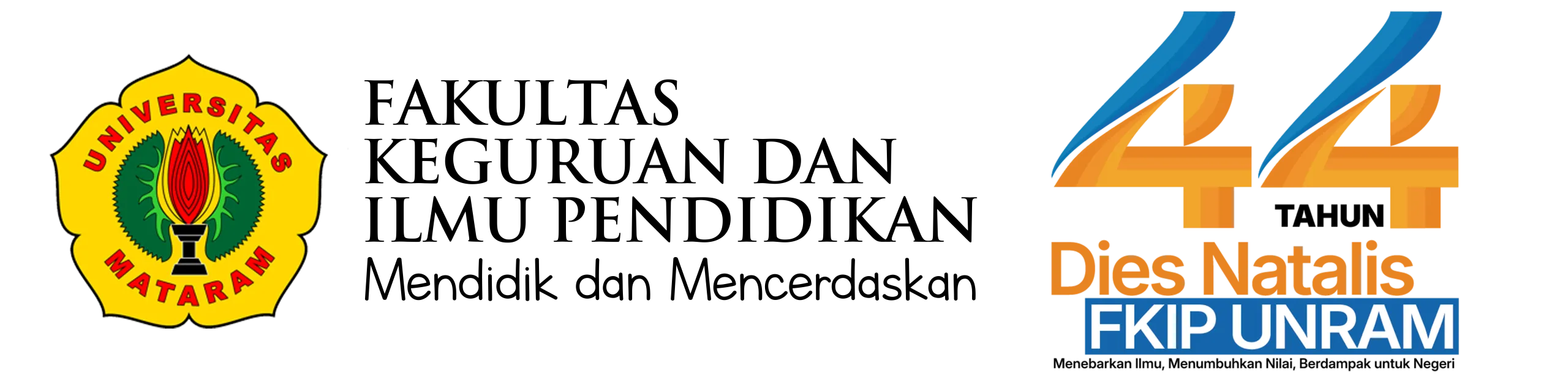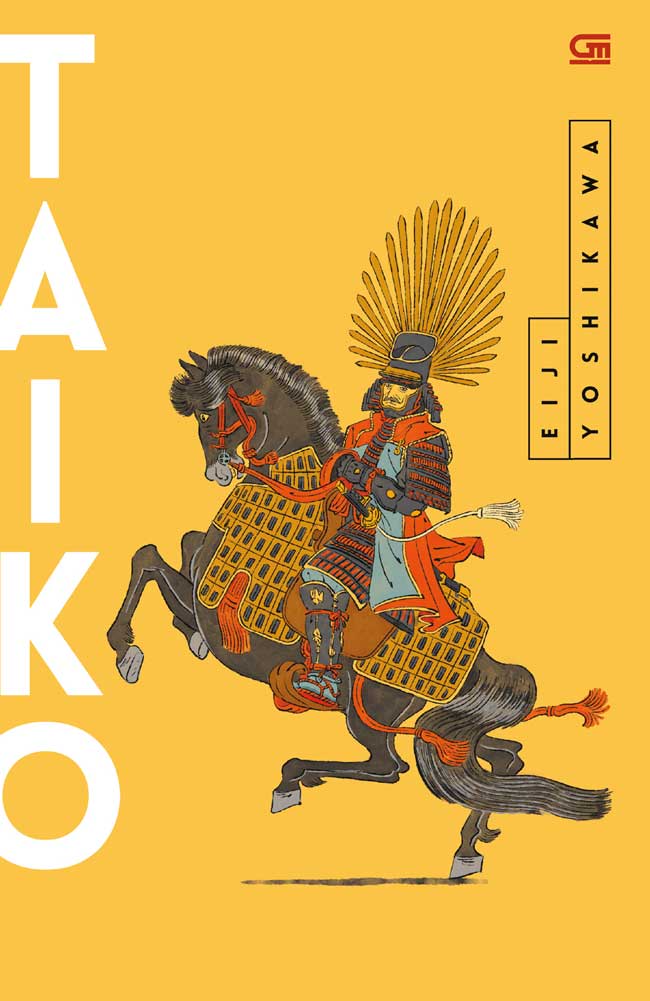

Penulis: Dr. Johan Mahyudi, M.Pd.
Halaman-halaman paling awal dari novel Taiko karya Eiji Yoshikawa, berisi peta kekaisaran Jepang di abad ke-16, model penghitungan waktu siang-malam menurut jam tradisional Jepang dan sebuah catatan penting mengenai falsafah hidup tiga orang panglima yang sama-sama ingin mempersatukan Jepang, tapi berbeda dalam cara untuk mewujudkannya. Falsafah-falsafah mereka yang berlainan itu sejak dulu diabadikan oleh orang Jepang dalam sebuah sajak yang diketahui oleh setiap anak sekolah di Jepang.
Sajak itu berbunyi:
Bagaimana jika seekor burung tak mau berkicau?
Nobunaga menjawab, "Bunuh saja!"
Hideyoshi menjawab, "Buat burung itu ingin berkicau.”
leyasu menjawab, "Tunggu."
Novel Sejarah Taiko berkisah tentang laki-laki yang membuat burung itu ingin berkicau.
Walaupun tebalnya 1144 halaman dalam tulisan latin berbahasa Indonesia, dan empat kali lebih tebal dalam huruf Hiragana, Katakana dan Kanji, Taiko amat bagus untuk dibaca. Yoshikawa tidak saja berhasil mengurai dengan sangat mendalam tentang teknik dan emosi dari setiap pertarungan-pertarungan di medan pertempuran, tapi dengan sangat apik, diatur dalam tempo yang sangat lambat untuk mengurai konsekuensi dari falsafah hidup yang dipilih oleh setiap orang. Nobunaga, seorang panglima yang gegabah, tegas, brutal, menerima kekalahan sekaligus kematiannya Ketika perang masih sedang berkecamuk. Hideyoshi, seorang panglima yang sederhana, halus, cerdik, dan kompleks, berhasil menjadi Taiko, penguasa absolut di seluruh kekaisaran Jepang; kemudian Ieyasu, yang selalu tenang, sabar, dan penuh perhitungan, berhasil mempertahankan eksistensi kekuasannya di tengah bayang-bayang kekuasaan Sang Taiko.
Kisah tentang Taiko, dan dua panglima perang lainnya, tidak hanya dapat dinikmati melalui penuturan Yoshikawa, tapi tersebar dalam sejumlah buku cerita, dan bahkan komik, juga film, yang semuanya dapat diakses oleh anak-anak sekolah di Jepang, dalam bentuk program pemberian buku geratis yang di sekolah dijadikan sebagai materi dalam kurikulum mereka.
Indonesia, seperti Jepang, juga merupakan bangsa yang memiliki banyak teladan dari masa lalu, dan ada banyak falsafah kehidupan yang dapat dipetik dari perikehidupan mereka. Hanya saja, dalam konteks Indonesia, falsafah seolah terhenti hanya pada diskusi tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika untuk mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman agama, suku, dan bahasa. Kemudian di dunia Pendidikan, ada falsafah Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Bagaimanapun, konsep ideal ini, besama konsep-konsep ideal lainnya yang pernah diajarkan di sekolah harus segera ditransformasi ke dunia nyata.
Siapa sosok dari masa lalu yang kehidupannya pernah benar-benar dijalani untuk menghikmati Bhinneka Tunggal Ika? Mungkin adalah contoh pertanyaan paling awal yang harus diajukan untuk melahirkan buku-buku yang akhirnya akan membuat anak-anak sekolah lebih bisa memahami falsafah tersebut. Bukankah lebih baik jika falsafah itu akhirnya diketahui didorong oleh pengalaman heorik sosok-sosok teladan dari Nusantara?
Literasi Indonesia yang tercatat selalu berada di peringkat bawah, selalu menjadi fakta yang menggoda untuk membangun menara tuduhan ke sejumlah pihak. Tapi untuk apa? Sudah banyak tuduhan dilontarkan dan para tertuduhnya seperti tidak bergeming. Karena itulah, di hari buku ini, dalam Bahasa yang sederhana, perlu kiranya disampaikan sebuah penutup yang biasa-biasa saja. Kalau selama ini Jepang sering tercatat sebagai negara peringkat lima besar dalam literasinya karena pemerintahnya menyediakan beragam buku bacaan menarik di sekolah, pemerintah Indonesia juga pasti bisa melakukannya.
Anak-anak di sekolah tidak bisa didorong untuk membaca sementara ketersediaan buku bacaannya terbatas. Kalau di Jepang buku bacaan menjadi materi pelajaran, di Indonesia juga perlu seperti itu, guru jangan hanya mengajarkan apa yang ada di buku teks saja. Kalau di Jepang, tempat-tempat membaca mudah dijangkau, harga buku juga terjangkau, mengapa di Indonesia tidak bisa? Pasti bisa, kalau diniatkan, dan semua lembaga yang terkait dengan perbukuan, tidak saling menunggu, atau menyimpan program bagus mereka nanti yang tidak perlu lagi dinantikan.
Kalau di Jepang mereka banyak menerbitkan buku-buku terjemahan, di Indonesia kenapa tidak? Lewat buku-buku terjemahan, dengan cepat, masyarakat Indonesia bisa mengenali dunia, lewat ribuan cerita mempesona. Pemahaman akan falsafah dari berbagai belahan dunia pada akhirnya akan mendorong generasi Indonesia menjadi lebih peka terhadap perikehidupan masyarakat global. Bukankah itu menjadi jalan untuk lebih bisa ikut serta dalam menjaga kedamaian yang abadi? Bukankah itu sudah Pancasialis?
Dan satu lagi, kalau di Jepang, pada hari buku, pemerintah membagikan buku geratis, masa Indonesia tidak bisa?